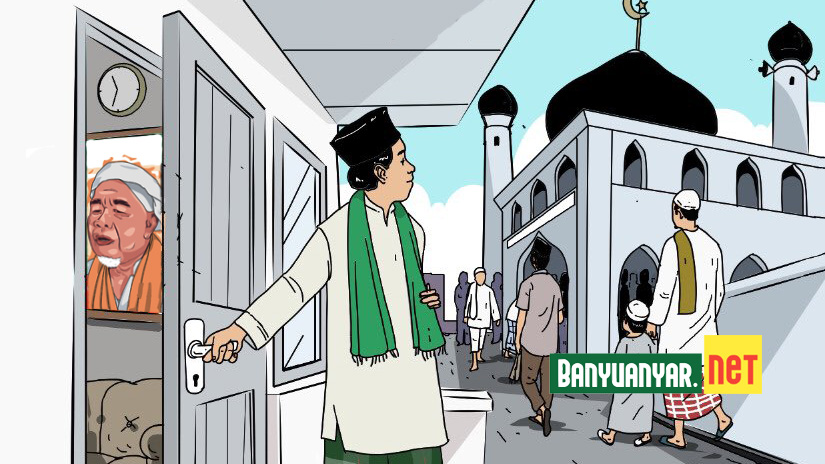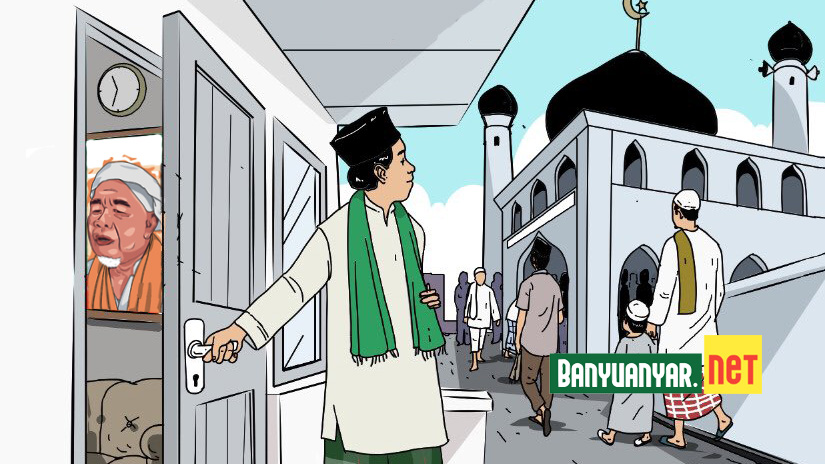Cerpen: Kasyaf Kiai (3)
By: Ach. Jalaludin | 09 September 2023 | 712
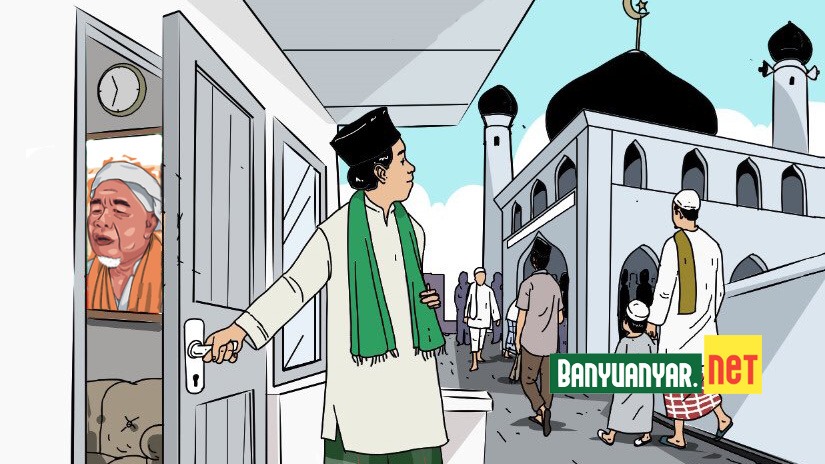
ilustrasi oleh @achjalaludin
Masih banyak santri yang kurang memperhatikan lembaran-lembaran kitab kuning yang memenuhi sudut-sudut asrama. Seperti terlihat menyumbat lubang-lubang kayu atau tembok yang berkubang. Mungkin niatnya memuliakan kitab dan ilmunya, tapi cara seperti ini seolah tanpa niatan, hanya setengah-setengah saja, yang penting tidak di bawah. Padahal seharusnya diletakkan di tempat yang dimuliakan sebagaimana kemuliaan ilmu. Sebab itu dengan penuh kesadaran aku selalu menyempatkan memunguti sobekan atau lembaran yang tidak sengaja jatuh untuk kuletakkan di tempat yang semestinya.
Itu juga merupakan pesan almarhum Kiai Sepuh untuk senantiasa memuliakan ilmu dan apa-apa yang berhubungan dengan ilmu. Juga menghormati ahlul ilmi dan apapun yang berhubungan dengannya. Tentu semua orang mempunyai cara masing-masing untuk menghormati sesuatu, tapi yang jelas dalam mengerjakan ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan cara ikhlas dan sempurna.
Selain memperhatikan lembaran atau sobekan kitab yang tanpa sengaja tergeletak di tempat yang kurang layak aku juga berusaha istiqamah membantu pesantren untuk membersihkan lingkungan pesantren. Sampah juga harus menjadi perhatian utama, dari ribuan santri setiap hari bisa menghasilkan lebih dari satu sampah setiap satu orang santri. Maka dapat dipastikan setiap hari sampah yang berserakan adalah dua kali lipat dari jumlah santri yang ada. Untuk itu menjaga kebersihan pesantren baik dari sistem dan pengendalian barang-barang yang menyisakan sampah harus diperhatikan lebih serius.
Aku menyingsingkan lengan baju, meletakkan kopiah pemberian Kiai Sepuh yang sampai saat ini kujaga. Kuperhatikan tempat sampah yang hampir semuanya penuh, saatnya aku membersihkan pesantren.
“Maaf ya, Kang,” ucap seorang santri meletakkan sampah dalam tempat sampah yang hendak kuangkat. Rupanya dia adalah Pramudya, santri yang kadang sering menyapaku setiap pagi, kadang kita berdiskusi.
“Tidak apa-apa, mungkin masih ada sampah lainnya sebelum Kang Didin pergi,” jawabku sembari tersenyum lebar, seolah menganggap santri tadi anakku sendiri. Perihal menganggap santri sebagai anak, aku teringat ketika aku berbincang dengan Ustaz Sanjab. Saat itu dengan iseng aku bertanya kenapa kalau berkendara motor di jalanan pesantren sangat lirih sekali, padahal ketika di luar pesantren kadang kecepatannya di atas rata-rata, sangat berbeda dengan Ustaz Sanjab ketika di pesantren.
‘Saya ingat dengan pesan kiai sepuh, beliau berpesan untuk menganggap santri seolah-olah anak kita. Jadi kalau di pesantren harus hati-hati, takutnya ada santri tak sengaja berlarian atau tiba-tiba di tengah jalan, nanti membahayakan mereka,’ jawab Ustaz Sanjab.
“Ini, Kang,” Pram datang dengan sampah lebih banyak membuatku susah melebarkan senyum.
“Kenapa kau tidak bantu Kang Didin saja membuang sampah?”
“Hahahah! Tidak bisa, Kang. Aku masih mau menemui Ustaz Sanjab.”
“Tumben ada yang mau menemui Ustaz Sanjab, dalam rangka apa?” Tanyaku dengan heran, baru kali ini ada santri yang mengatakan secara langsung ingin menemui beliau.
“Urusan pribadi, Kang. Ya sudah aku duluan, Kang!”
Pram langsung meninggalkanku yang sibuk merapikan sampah karena tidak muat ditambah sampah Pram tadi. Anak ini selalu membuat orang sibuk, tingkah lakunya akhir-akhir ini selalu berurusan dengan pihak keamanan pesantren. Entah apa yang membuatnya seperti itu, tapi sepertinya Pram begitu ketika aku dan dia berdiskusi tentang kasyaf kiai.
Membicarakan kasyaf merupakan diskusi yang tidak pernah selesai di antara santri. Yang selalu menjadi referensi para santri adalah Ustaz Sanjab Daholi. Meski sebenarnya apa yang mereka kutip dari beliau tidak sempurna. Apa yang beliau maksud sempat menjadi obrolan serius di antara aku dan beliau. Sesama santri yang dulu pernah satu generasi, aku tahu betul apa yang beliau maksud.
Yang beredar di lingkungan santri hanyalah anggapan bahwa kasyaf adalah ketika seseorang dapat mengetahui segala apa yang tengah diperbuat oleh orang lain. Seseorang yang memiliki keutamaan kasyaf seperti orang yang kapan saja dapat mengetahui perbuatan orang lain dengan tanda-tanda di tubuhnya. Sebab itu santri selalu takut bertemu Kiai kalau mereka melanggar peraturan pesantren.
Dari mereka banyak mendapati cerita yang mengisyaratkan Kiai memiliki keutamaan yang mereka maksud. Ada yang mengatakan ketahuan melanggar merokok, keluar tanpa izin, dan nakal dalam melaksanakan aturan dan kewajiban pondok pesantren. Aku tidak tahu kebenaran cerita mereka, hanya bisa husnuzan pada Kiai, bahwa Kiai akan selalu mendidik santri-santrinya dan akan selalu menjadi orang pertama yang menjaga kemaslahatan umat.
Aku juga Ustaz Sanjab sendiri tahu dan percaya bahwa kasyaf itu memang benar adanya. Banyak sekali tokoh tasawuf yang menyinggung tentang hal ini karena memang merupakan bagian karomah yang Allah berikan pada hambanya yang Allah pilih. Para hamba yang mendapatkan karamah merupakan ahlu sir, yaitu orang yang diberi keutamaan untuk mengetahui rahasia Allah di antara hamba-hambanya. Semua yang berkaitan dengan hal itu murni menjadi kehendak Allah sendiri dan kita sebagai hambaNya tidak tahu pada siapa keutamaan itu Allah berikan.
Kasyaf tidak hanya sebatas anggapan sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah santri. Kasyaf adalah dibukanya tirai ilahi hingga mengetahui rahasia-rahasia Allah. Bentuknya beragam. Ada yang tahu kapan orang tersebut akan meninggal, apa yang akan terjadi di masa depan, mengetahui sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indra hingga mengetahui hakikat dari sesuatu.
Tentu keutamaan seperti ini tidak sembarang orang yang memilikinya, Allah sendiri menyinggung dalam al-Qur’an bahwa Allah yang mengetahui hal yang gaib dan tidak ada seorangpun yang bisa mengetahuinya kecuali utusan yang Allah ridai. Sebab itu para tokoh tasawuf berpendapat untuk mengetahui apakah seseorang itu layak disebut mendapatkan keutamaan tersebut, lihatlah amalnya. Apakah amal yang setiap hari orang itu kerjakan sesuai dengan syariat atau tidak. Apakah orang itu merupakan orang yang shalih atau orang yang fasik.
Seorang tokoh tasawuf yaitu Abul Hasan as-Sazdili mengatakan, “kalau seseorang mendapatkan kasyaf, namun kasyaf tersebut bertentangan dengan nash, maka tinggalkan kasyaf tersebut kemudian ikuti nash tersebut.” Alasannya karena nash itu sudah tentu dijamin kebenarannya oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan kebenaran kasyaf yang bertentangan dengan nash tidak ada yang menjamin kebenarannya. Bisa saja itu merupakan godaan jin atau setan.
Apa yang terjadi pada Syekh Abdul Qodir Jailani ketika itu merupakan bentuk kehati-hatian beliau dalam melihat kebenaran tentang keutamaan yang dartangnya dari Allah atau dari setan. Ketika itu beliau didatangi oleh sebuah caya yang berkilau. Tampak seolah cahaya ilahi yang menghampiri, seraya mengatakan, ‘Hai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu, aku datang kepadamu untuk menyatakan bahwa kini aku telah menghalalkan segala yang tadinya aku haramkan!’
Mendengar hal itu, Syekh Abdul Qadir berteriak membentak: “Ikhsa’ ya Lien! Keparat kau setan, enyah kau dari mukaku”. Seketika padamlah cahaya yang menyilaukan itu. Dari cerita itulah kita belajar bahwa melihat berbagai keutamaan yang didapat harus sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Hadis. Kalau tidak berarti itu dari setan dan selainnya.
Beberapa hari ini aku banyak berbicara tentang kasyaf, apa lagi membawa nama Kiai. Memang beberapa kali aku bergaul dengan keluarga thelem, seperti Kiai Sepuh dan Gus Badrun seolah aku diperlihatkan mengenai kasyaf mereka. Meski begitu aku hanya berbaik sangka saja, kasyaf dan karomah lainnya bukan menjadi urusan hambaNya. Jadi pada siapa karomah itu diberikan, aku tidak tahu. Tapi yang setiap hari Kiai dan Gus Badrun lakukan selalu membuatku lebih dekat kepada Allah.
Meski aku tidak tahu apakah beliau mempunyai kasyaf sebagaimana anggapan orang-orang, tapi menghadap beliau dengan keadaan penuh rasa bersalah dan kemurungan membuatku merasa malu. Karena pernah aku menghadap Kiai Sepuh beliau mengatakan, ‘merasa bahagia karena rahmat dan ampunan Allah lebih baik dari pada murung karena memikirkan dosa.’ Kadang terlalu banyak mengingat kehidupan beliau membuat mataku berkca-kaca, allah yarham, Kiai.
Akhirnya selesai juga membersihkan halaman pesantren yang memang setiap hari aku bersihkan. Halaman lainnya biasanya dari pihak santri yang memang tergabung dalam gerakan bersih pesantren. Membersihkan pesantren di waktu pagi merupakan keinginanku sejak awal, dan itu kulakukan secara sukarela. Mungkin tidak seberapa, tapi perhatianku pada kebersihan dan memuliakan apapun yang berhubungan dengan ilmu seolah mempunyai rasa nyaman pada jiwaku. Di tengah usia yang mulai bertambah, dan kesibukan untuk mengurus rumah tangga, mungkin amalan inilah yang dapat kulakukan sebagai bekalku di akhirat kelak.
“Sudah mau pulang, Kang?” Tiba-tiba Pram menyapaku di tengah aku sedang memberesi alat-alat kebersihan. Membersihkan pesantren sambil merenung membuat pekerjaan ini terasa cepat.
“Iya, Pram, kamu bagaimana dengan Ustaz Sanjab? Tumben ada santri yang mau berbicara langsung dengan beliau.”
“Urusan pribadi, Kang.”
“Kamu punya hutang pada beliau?” Aku tahu tujuan Pram bukan itu. Beberapa hari lalu sepertinya dia tidak masuk daftar kelulusan.
“Itu Kang, negosiasi terkait pengabdian kelas akhir,” jawab Pram mengakui maksudnya sambil tersenyum malu.
“Hahahh, terus beliau bilang apa?”
“Akhirnya saya lulus, meski ada beberapa persyaratan.”
Pram sepertinya lega, karena dari kemarin dia selalu berurusan dengan pihak keamanan soal pelanggaran yang dia perbuat. Sebab itulah namanya tidak ada dalam daftar kelulusan. Pram di antara santri lainnya mungkin terbilang pintar, bahkan dia selalu diskusi mengenai persoalan fikih dan tauhid yang dia pelajari di madrasah. Pandangannya mengenai disiplin keilmuan cukup menarik, bahkan mengenai kasyaf. Sangat berbeda dengan Ahmad, teman satu kamarnya yang pada akhirnya juga memiliki pandangan lebih baik pada banyak hal.
Banyak santri yang aku temui, begitu juga pelajaran yang kudapati. Sebanyak itulah aku menjadi sadar bahwa ilmu di pesantren ini tidak hanya soal apa yang tertulis dalam kitab dan buku, tetapi juga apa yang tertulis di sudut-sudut pesantren.
Aku meninggalkan Pram untuk pulang, belum jauh kuberjalan, Pram memanggilku dari depan kamarnya,
“Kang Didin! Kopiahnya ketinggalan,” Pram melambaikan tangannya sambil memegang kopiahku, kopiah pemberian Kiai Sepuh.