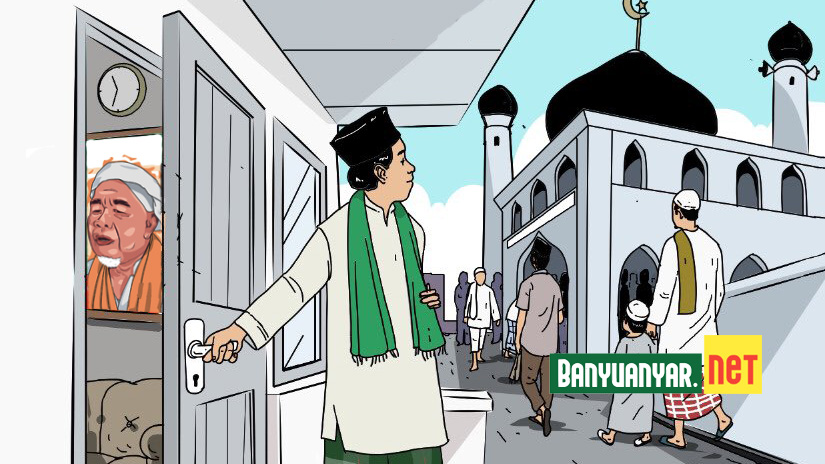Cerpen: Kasyaf Kiai (1)
By: Ach. Jalaludin | 17 Juli 2022 | 942
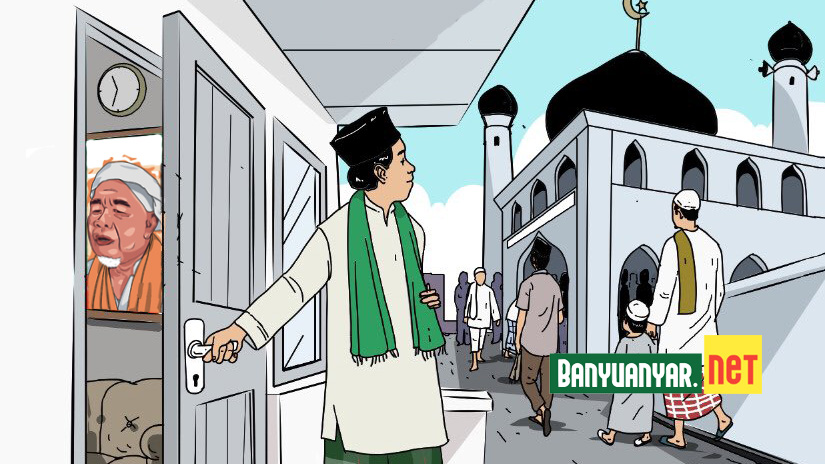
ilustrasi oleh achjalaludin
Semua santri tahu bahwa kiai mempunyai kekuatan keramat yang dapat mengetahui santrinya di manapun santrinya berada. Bukan hanya itu, kiai juga dapat mengetahui apa yang dikerjakan oleh seluruh santri dengan hanya melihat tanda di dahi. Menurut santri lama, setiap dahi santri terdapat tanda yang mengisyaratkan pekerjaannya, dan satu-satunya yang dapat membaca semua itu adalah kiai.
Tak jarang dari banyaknya santri yang melanggar langsung dipanggil ke thelem kemudian diberdirikan sambil membaca al-Qur’an. Tergantung pelanggarannya, ada yang bahkan disuruh menghatamkan al-Qur’an ke asta thelem, yaitu tempat para pendahulu pesantren disemayamkan.
Mungkin sebab itulah para santri takut untuk melanggar aturan pesantren. Setiap ingin melakukan pelanggaran, maka terbesit kiai sedang mengawasi dari suatu arah. Bahkan ustadz keamanan di pesantren pernah bilang, “yang paling mudah di pondok ya jadi keamanan, karena kalian itu tidak jauh dari pengawasan kiai juga. Kalian itu seperti ikan dalam kaca”.
Sebenarnya itu dulu juga pernah diucapkan Ustadz Sanjab Daholi, salah satu ustadz yang paling disegani karena kesepuhannya mengajar di pesantren. Kata beliau, seluruh santri tak ubahnya ikan dalam kotak kaca bagi kiai, bagaimana ikan dalam kaca? Ikan dalam kaca dapat dengan jelas dilihat dari luar, mau berjalan, makan dan melakukan apapun kita dapat dengan mudah melihatnya.
Aku dan teman-teman pernah dipanggil langsung ke thelem. Padahal tidak ada satupun yang tau bahwa aku melakukan pelanggaran itu. Sebagai orang yang sering merokok sejak sebelum mondok, melihat kesempatan sedikit saja jadi lupa dengan aturan pesantren dan keramat kiai.
Saat itu selesai kami dikunjungi orang rumah, ternyata ada satu bungkus rokok yang tertinggal di kamar. Mengetahui itu aku langsung menyimpannya dalam beras yang merupakan jatah kiriman setiap bulan, takut ada kontroling dari keamanan. Pesantren ini memang salaf, setiap santri biasa dikirimi beras barang tiga hingga lima kilo setiap bulan. Kecuali santri dari keturunan orang kaya, biasanya berlangganan nasi kotak pada tetangga sekitar pesantren.
Tepat malam potan, malam libur kegiatan pesantren setiap malam Selasa dan Jumat kami berencana memasak makanan ke dapur seperti kebanyakan santri lainnya. Dapur terletak di sudut pesantren, cukup jauh dari asrama karena santri memasak menggunakan kayu bakar dan kompor dengan minyak tanah. Masakannya beragam, Kadang goreng lele bagi yang punya uang, atau telur dan mi instan sepertiku malam ini. Budi mempunyai tugas memasak nasi, sedang aku dan Pram ke toko beli mi dan telur.
Malam itu ketika sudah banyak santri meninggalkan dapur, setelah kami menghabiskan makanan yang kami masak, Budi malah mengeluarkan sesuatu dari sarungnya.
“Mad, kau tau ini milik siapa?” Budi menunjukkan bungkusan yang mudah kukenali, beberapa hari lalu aku menaruhnya di karung beras. “Aku menemukan ini di berasmu loh..” lanjut Budi karena aku tak menjawab pertanyaannya.
“Itu ketinggalan, milik bapaknya Kasan santri baru itu!”
“Sungguh?” Budi masih menyelidik.
“Sumpah!” ketusku. Sehabis aku katakana itu, malah Pram merampas rokok di tangan Budi.
“Tak penting ini milik siapa, sekarang ini sudah milik kita!”
Pram langsung merobek bungkusnya dan mengeluarkan beberapa batang rokok.
“Lihat, ini hanya tiga batang, berarti ini memang untuk kita.”
Entah kenapa malam itu aku tidak bisa menolak ajakan Pram dan rayuan Budi. Padahal aku juga sempat menjelaskan kemampuan kasyaf kiai yang dijelaskan Ustadz Sanjab, mereka malah tidak memedulikan ucapanku. Bagi Pram itu akal-akalan pengurus untuk nakut-nakuti santri agar tidak melanggar.
Di tengah tungku yang masih menyala, Pram mengambil batang kayu dengan bara apinya.
“Kalian tau, sekarang pengurus dan keamanan sedang rapat bulanan, jadi tidak akan ada kontroling. Ayok ke belakang dapur saja!”
Malam itu kami tidak mempedulikan apapun, menikmati setiap hisapan rokok dan menghembuskannya dari hidung.
Pagi harinya, sebelum kami berangkat ke madrasah, pihak keamanan mendatangi kami dan menyuruh kami menemui kiai ke thelem. Kami saling tatap dan menunjuk Pram, “ini salahmu,” kataku dengan nada menekan.
“Kamu juga merokok, kan?” Pram balik menajamkan mata.
“Bukankah aku sudah katakan bahwa kiai pasti dapat mengetahui kelakuan kita malam itu, tapi kamu tidak ingin tau!”
“Lalu mengapa kamu ikut merokok? bukankah itu rokok yang kau simpan sendiri?”
“Iya kalau Budi tidak mengambilnya!” Aku menunjuk Budi.
“Aku hanya membawanya, tapi Pram yang membukanya, dia juga yang mengajak kita kan?” Budi juga tidak ingin mengakui kesalahannya. Aku mendekati Pram, membuat jarak yang lebih dekat. Ingin rasanya aku pukul wajah bodoh menyebalkan itu. Namun Pram balik mendekatiku,
“Kau mau apa?”
Benar saja, kekesalanku memuncak, mengepalkan tangan untuk kudaratkan pukulan di wajahnya. Tapi sebelum itu kulakukan, keamanan masuk kembali ke kamar.
“Kalian dengar!? Cepat ditunggu kiai di thelem!”
Dengan berat hati kami berangkat memenuhi panggilan kiai. Sesampainya di thelem, kami masih cukup lama berdiri di bawah pohon angsana menunggu kiai. Kemudian kiai datang menemui kami dengan wajah seolah tanpa ekspresi. Beliau memperhatikan wajah kami. Percaya atau tidak, saat itu aku memakai songkok putih yang aku kerutkan untuk menutupi dahi. Karena aku setengah percaya dengan anggapan santri lama bahwa beliau dapat mengetahui pelanggaran santri dari tanda di dahinya.
Beliau menghampiri kami satu-satu. Pada Budi beliau berkata, “pintar-pintarlah memilih teman.” Kemudian beliau menuju Pram, “berapa kali kau berdiri?”
“Cukup sering kiai”.
Lalu beliau menemuiku, sungguh saat itu aku gemetar, apa lagi beliau cukup lama di depanku. “banyak-banyaklah belajar.” Tak kusangka beliau juga membetulkan songkokku yang berkerut hingga dahiku terlihat. “Kalau shalat harus begini,” tambah beliau.
Setelah itu beliau menyuruh kami menemui keamanan di kantor. Sesampai di kantor keamanan tidak banyak bicara, beliau mengambil gunting kemudian menggunduli rambut kami satu-satu. Beliau juga memaksa kami berdiri di depan kantor di atas sebuah meja dengan memakai kalung yang bertuliskan “MEROKOK”.
Pagi itu kami benar-benar menjadi pusat perhatian para santri, beberapa memandang sinis menandai wajah kami. Aku sangat menyesal dengan apa yang telah kulakukan malam itu. Dalam hati aku menyalahi Pram, kalau saja dia tidak bodoh dan mau mendengarkan ucapanku. Tapi setiap kali aku menyalahkan Pram, dia malah balik bertanya, “bukankah kamu yang menyimpan rokok itu?” Saat itulah aku tidak berteman lagi dengan Pram, beberapa kali aku melihat dia berdiri di depan kantor dengan pelanggaran yang berbeda. Mungkin itu akibat dia tidak percaya dengan kekuatan kasyaf yang dimiliki kiai.
Dari peristiwa itulah aku percaya bahwa kiai benar-benar mempunyai kemampuan kasyaf sebagaimana dijelaskan Ustadz Sanjab. Di mata kiai, santri tak ubahnya ikan dalam kaca. Beliau mengetahui apa saja yang dikerjakan semua santri. Bukan cuma aku, beberapa santri bahkan ada yang dikeluarkan dari pesantren gara-gara janjian dengan seorang gadis yang rumahnya tak jauh dari pesantren.
Tapi yang membuatku heran dan kesal, Kang Didin malah tidak percaya dengan anggapan itu, bahkan sikapnya seolah lebih pintar dari kiai. Padahal di pesantren dia hanya sebagai tukang sapu saja. Tiap pagi, baru habis subuh dia dan tukang sapu lainya sudah melakukan tugas mereka membersihkan sudut-sudut pesantren. Bukan hanya waktu pagi, kadang malam hari dan habis acara pesantren Kang Didin terlihat sibuk dengan sapunya. Mungkin suka-suka Kang Didin saja untuk membersihkan pesantren, kemudian membuangnya dengan truk yang entah ke mana mereka buang.
Tapi itu, sikapnya pada kiai membuatku jauh lebih kotor dari sampah yang setiap hari Kang Didin bersihkan. Bagaimana tidak, pernah aku berdebat dengan dia tentang keramat yang dimiliki kiai, dia malah tertawa dan menganggapku bodoh.
“Bukan Kang, bahkan Ustadz Sanjab saja percaya bahwa kiai punya kekuatan keramat. Beliau bilang itu kekuatan kasyaf yang tidak sembarang orang memilikinya!” Ketusku dengan suara meninggi.
“Iya, kalau Tadz Sanjab bilang begitu itu benar, tapi kalau kamu yang mengucapkan itu jadi salah!” Bantah Kang Didin sambil meledek. Bagiku dia tak ubahnya Pram yang ingin mencelakai temannya. Parahnya, Kang Didin juga mengejekku, “bukankah kamu juga pernah berdiri gara-gara merokok, apakah itu juga kasyaf kiai?”
***
Pagi-pagi aku senang sekali setelah melihat papan pengumuman pesantren. Di situ tertulis namaku di deretan santri kelas akhir yang lulus ujian baca kitab untuk menjalani masa pengabdian selama satu tahun di lembaga dan pesantren yang membutuhkan tenaga pendidik. Di tengah jalan ketika aku ingin kembali ke kamar, kulihat Kang Didin sibuk membersihkan halaman depan kamarku. Dia terlihat sangat hati-hati, beberapa kali memunguti sobekan kertas kemudian meletakkannya di tempat yang layak.
Tapi mengingat sikap Kang Didin yang kurang ta'dzim pada kiai karena tidak percaya dengan kasyaf kiai membuatku sedikit jengkel. Belajar dari pengalamanku sendiri ketika aku tidak percaya dengan kasyaf kiai, aku malah sering melakukan pelanggaran pesantren, tetapi ketika aku percaya bahwa kiai sedang mengawasiku, malah aku bisa lulus dan layak mengikuti program pengabdian. Berbeda dengan Pram yang sampai sekarang tidak percaya, akibatnya, dia selalu berdiri di depan kantor dengan pelanggaran berbeda. Itulah mengapa dia tidak lulus untuk mengikuti program pengabdian.
Di depan kamar aku bertatapan dengan Kang Didin, “bersih-bersih, Kang?”
“Eh Mad, sini dulu!” Kang Didin mengajakku duduk di depan kamar, dia sama sekali tidak menjawab pertanyaanku.
“Kau dulu pernah berdiri kan?”
Aku tidak langsung menjawab, menyelidiki Kang Didin yang sepertinya ingin memulai perdebatan lagi.
“Kenapa Kang?”
“Sebenarnya yang memberitahu kamu merokok itu aku ke pengurus.”
“Terus?”
“Iya, saat itu ketika musyawarah pengurus baru selesai, aku dan teman-teman membersihkan kantor. Ketika ingin membuang sampah, aku melihat kamu dan dua temanmu di belakang dapur. Jadi aku laporkan ke pengurus. Oleh sebab itu Kang Didin minta maaf.”
Aku makin berpikir panjang, tapi melihat keseriusan Kang Didin minta maaf, aku langsung memaafkan.
“Jadi itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kasyaf kiai.” Tambah Kang Didin.
“Tunggu Kang, kalau minta maaf aku maafin, tapi soal kasyaf itu kiai memang punya!”
Lagi-lagi Kang Didin menyinggung soal kasyaf, tapi pikiranku seolah ada yang baru di situ meski aku belum bisa menyimpulkan.
“Bukan, menurutku begini..” Kang Didin merapikan duduknya. “Masalah kasyaf atau tidaknya kiai itu tidak ada yang tau kecuali Allah, bisa saja iya, bisa saja tidak. Artinya kita tidak bisa memastikan apapun tentang seseorang, apalagi hal gaib seperti ini, hanya Allah yang mengetahui hal gaib.”
“Maksud Kang Didin?”
“Kau tau Ridwan Tals?” Kang Didin balik bertanya, aku hanya diam. Tentu aku tau musisi legendaris itu. “Iya, dia seorang musisi yang berbakat. Dalam musiknya bersuara tentang keadilan, kemiskinan, romansa dan demonstrasi utamanya di era Orba. Bahkan tanpa ragu menuliskan tikus-tikus berdasi dalam liriknya. Dia diidolakan oleh hampir seluruh penduduk negeri ini. Lahirlah konser terbesarnya 30 tahun lalu.
“Tapi itulah yang membuat dia sekarang dibenci oleh banyak orang. Era sekarang bukan Orba lagi. Di kala umurnya yang menua, rambutnya tak lagi panjang seperti dulu, dipenuhi uban yang menggambarkan usianya. Petikan gitarnya pun pelan, suaranya serak tapi damai, lagu-lagunya tidak mengkritik kekuasaan lagi, lebih banyak tentang kerohanian dan perdamaian.
“Dengan kondisi Ridwan Tals yang seperti itulah banyak orang membencinya. Mereka yang menaruh harapan pada Ridwan menuntut, harusnya Ridwan seperti dulu, mengkritik kekuasaan bukan malah menjilat kekuasaan. Mereka menganggap sikap Ridwan berubah karena dikasih uang oleh kekuasaan. Merekalah orang-orang yang mengharuskan orang lain untuk sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan ketika tokoh yang diidolakannya tidak sesuai, maka yang asalnya cinta berubah menjadi kebencian, yang asalnya kagum akan berubah menjadi kekecewaan. Mereka juga orang yang memberikan ukuran kepada orang lain sesuai hawa nafsunya.”
Aku tertegun mendengar cerita sekaligus penjelasan Kang Didin, di balik kesehariannya yang hanya tukang sapu pesantren ternyata mampu menjelaskan hal semacam ini. Sedikit-banyak aku mulai mengerti maksud Kang Didin. Tentang kasyaf kiai itu, mungkinkah hanya aku yang beranggapan terlalu tinggi pada kiai? Apakah aku juga termasuk orang yang memberikan ukuran terhadap orang lain sesuai nafsuku?
“Bukan hanya seorang musisi,” Kang Didin masih melanjutkan, “dulu juga ada orang yang saleh keturunan seorang khalifah yang mulia. Semua orang menginginkan dia yang harus menggantikan ayahnya karena diturunkan dari jabatannya secara zalim. Dari satu wilayah ke wilayah lainnya menggema namanya. Mereka menginginkan orang saleh itu menemui mereka untuk dapat berbaiat kepadanya.
“Sungguh dia memang orang saleh yang baik sekali. Dengan beberapa pertimbangan dia ingin menemui orang-orang itu dengan membawa rombongan. Dari keluarganya ada yang melarang. Bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam, kakeknya yang mulia juga sudah pernah mengisyaratkan takdir itu. Benar saja, di suatu wilayah dia dihadang oleh pasukan pemerintah, dan di situlah takdir itu terjadi. Sungguh malang, orang saleh itu harus terbunuh.
“Jadi tidak baik memberikan ukuran pada orang lain. Kiai juga pernah menyampaikan, berdoalah juga untuk tidak mengetahui aib gurunya, karena ketika kita mengetahui aib gurunya, bisa saja kita kurang ta'dzim kepadanya. Cukup diakui saja bahwa kasyaf itu ada, tetapi pada siapa kasyaf itu dimiliki kita tidak tau, hanya Allah yang tau. Hingga nanti ketika kita melakukan kebaikan bukan semata-mata ingin dianggap baik oleh kiai, atau ketika kita tidak melanggar bukan karena ingin dianggap patuh oleh kiai, tapi semata-mata karena ada Allah yang mengawasi kita.
“Aku jelaskan ini karena kau sudah kelas akhir, takut kalau aku jelaskan dulu kau akan menjadi santri nakal. Paling tidak anggapan keliru itu dapat menjagamu untuk tidak nakal di pesantren.”
“Memang Kang Didin pernah jelaskan juga pada santri sebelumnya?”
“Iya.”
“Siapa?”
“Pram.”
Aku mengangguk sambil tersenyum. Kali ini Kang Didin membuatku terdiam cukup lama, sekarang aku benar-benar mengerti apa yang hendak Kang Didin sampaikan. Mungkin inilah mengapa dulu ketika aku dipanggil ke thelem kiai mengatakan, “banyak-banyaklah belajar.” Apakah saat itu kiai sedang kasyaf padaku?