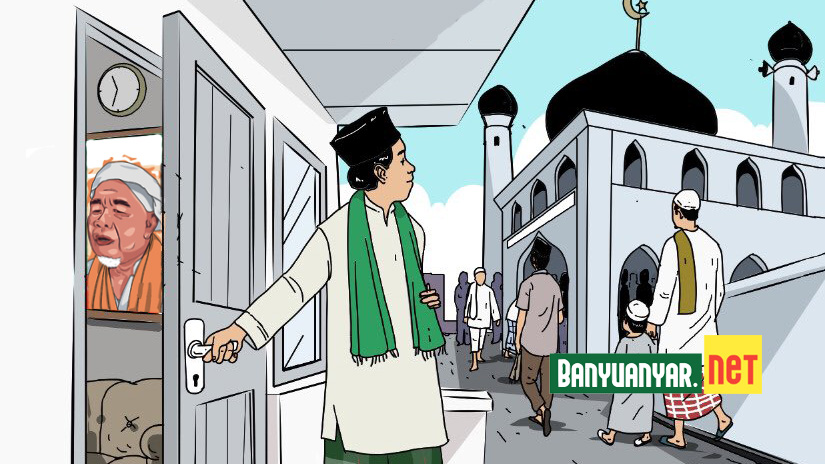Cerpen: Kasyaf Kiai (2)
By: Ach. Jalaludin | 02 September 2023 | 545
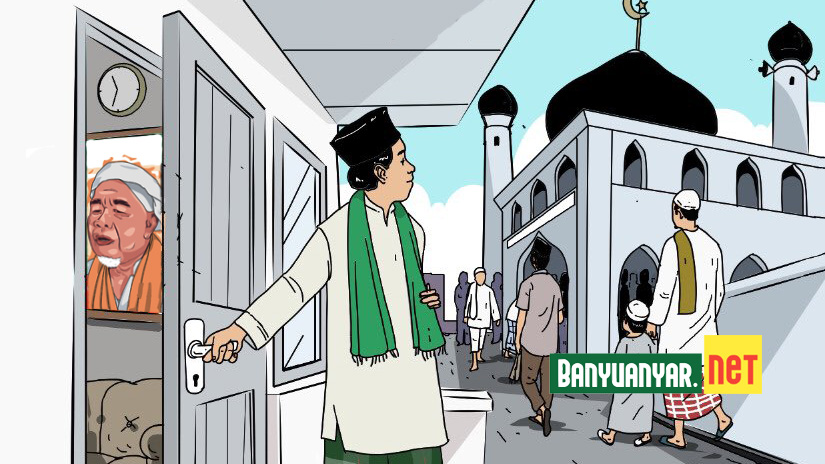
ilustrasi oleh @achjalaludin
Perpustakaan pesantren cukup ramai, ramai bukan dalam artian bising atau berisik, tetapi banyak santri yang berkunjung. Setidaknya dapat mengisi hampir separuh dari perpustakaan. Aku datang seperti biasa melihati wajah para santri yang terlihat fokus, padahal sangat mudah untuk mengajak ngobrol teman di sampingnya.
Itu yang membuatku heran, kenapa ya kita tidak boleh berisik di perpustakaan. Padahal kita bisa membuat perpustakaan terdengar begitu ramai. Bukan dengan bermain tentunya, tetapi berdiskusi, membicarakan tentang buku yang dibacanya atau kegiatan keilmuan lainnya. Itu bisa terjadi kalau pengurus perpustakaan pesantren ini tahu betul bagaimana membuat perpustakaan terkesan hidup. Tapi yang ada perpustakaan hanya terlihat sebagai penyedia buku saja bagi santri, tidak pernah menggalakkan para santri untuk senang membaca.
Aku mencari buku sembarangan, begitu malas sebenarnya bergaul dengan pengunjung perpustakaan yang kebanyakan seorang introvert, mereka mana mau diajak diskusi. Sebab itu aku mengambil salah satu buku yang sepertinya asyik, yaitu buku anekdot lucu. Mungkin dengan cara ini aku bisa tertawa.
Merasa cocok dengan buku yang aku pilih, aku langsung mencari tempat duduk. Belum sempurna aku duduk, ada seorang santri mendatangiku, dia terlihat buru-buru.
“Boleh minta tolong?” katanya, sepertinya aku sering melihatnya di masjid sebagai ta’mir.
“Iya apa?”
“Saya disuruh Kiai Badrun untuk meminjam buku terjemahan kitab Nashaihul Ibad.”
“Ooh, sebentar,” aku berdiri untuk mengambil buku yang dimaksud, menuju buku agama dan mencarinya. Dari seringnya aku ke perpustakaan, seolah aku mengetahui letak dan jenis buku yang tersusun di sini.
“Ini,” kataku sembari memberikan bukunya.
“Terima kasih.” Dia menerima bukunya, “tapi apakah tidak usah dicatat?”
Aku diam dengan ekspresi balik bertanya, “lagi tidak ada penjaganya, mungkin ambil saja, lagi pula ini disuruh beliau.”
Dia hanya mengangguk kemudian membalikkan badan untuk pergi. Sembari melihat dia keluar dari perpustakaan, aku berpikir kenapa Kiai meminjam buku di perpustakaan, bukannya beliau pastinya sudah mempunyai segudang koleksi. Yang dipinjam Kiai juga kitab terjemahan, padahal beliau juga mengampu kajian kitab Nashaihul Ibad.
Tapi mana ada yang tahu kehendak Kiai, apa yang sudah dikehendaki maka harus juga menjadi kehendak santri dan pengurus. Meski begitu yang dikehendaki Kiai juga memiliki makna dan maksud tersendiri. Karena memang seharusnya seorang kiai memikirkan kebaikan semua santri dan warga pondok pesantren.
Lebih dari itu banyak sekali dari santri yang berasumsi bahwa Kiai memiliki kasyaf yang tahu semua yang dilakukan santri, baik yang dilakukan secara sembunyi atau terang-terangan. Aku tidak tahu anggapan itu benar atau tidak, tapi aku meragukannya. Yang lebih mengherankan Kiai juga dianggap mengetahui bisikan hati seseorang, itu bisa dilakukan dengan hanya melihat dahi. Karena bagi Kiai, itu seolah memiliki tanda tersendiri dan mengisyaratkan bisikan hatinya.
Sudahlah, itu urusan Kiai dan orang-orang yang beranggapan seperti itu, yang bikin risih kalau melihat orang yang keterlaluan dan menganggap itu kebenaran tanpa mengetahui sendiri benar-tidaknya. Lebih baik kubaca saja buku yang tadi kuambil, sepertinya lucu.
Di halaman awal saja buku ini membuatku tertawa, bahkan dari beberapa pengunjung perpustakaan melihatiku sinis, mungkin karena ketawaku terlalu nyaring. Tapi biarkan saja, serius banget jadi orang!
Buku ini tipis, kecil, dan tentu saja ringan. Berisi cerita lucu, pantun, dialog lucu dan tebak-tebakan yang ada gombalnya. Ini anekdot lucu yang berkaitan dengan santri, jadi kalau tidak lucu bagi kalian bukan berarti bukunya yang kurang lucu, tapi kalian saja yang kurang mengerti. Aku kasih tahu beberapa tebak-tebakannya,
Apa persamaan kamu dengan peci? Jawabannya: sama-sama di kepalaku
Gang, gang apa yang bikin ustaz marah? Jawabannya: gangguin istrinya
Ayam apa yang besar sekali? Jawabannya: ayam semesta
Menurutku itu lucu sih. Ada juga cerita lucu ketika seorang pejabat datang ke pesantren. Oleh kiainya dibuatkan panggung untuk sambutan. Di acara itu ada santri yang tampil di atas panggung membacakan ayat al-Qul’an. Setelah turun kiai itu memanggil santrinya, di depan pejabat kiainya memberitahu,
‘Pak, ini santri masih sepuluh tahun tapi sudah hafal 30 juz,’
Terus pejabat itu jawab, ‘wah, bagus sekali, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Kalau begitu dilanjutkan ya sampai 40 juz.’
Bego sekali kan pejabatnya, tapi mana ada pejabat yang pintar, eh?.
Di tengah aku asyik membaca, saat itulah aku melihat Ahmad memasuki perpustakaan. Dia langsung menempati tempat duduknya sebagai pustakawan yang beberapa kali memang menjaga operasional perpustakaan. Mungkin asumsiku benar, kalau pengurus perpustakaan seperti Ahmad semua, susah sekali menjadikan perpustakaan terkesan hidup. Bukan merendahkan Ahmad, tapi begitulah Ahmad dengan pemikiran yang dia miliki.
Dan saat itu juga aku ingat kalau tadi ada santri yang meminjam buku karena disuruh oleh Kiai. Aku ingin memberi tahu, tapi malas. Biarkan saja, lagi pula perpustakaan ini milik Kiai juga. Ahmad terlihat meletakkan kitab dan serbannya, mungkin dia masih berlama-lama di masjid sebelum kemudian melakukan kewajibannya. Memang begitulah Ahmad.
***
Pagi sekali aku dibuat menguping perdebatan Kang Didin di depan asrama dengan Ahmad. Awalnya hanya saling menyapa, tetapi lama-kelamaan adu mulut terjadi. Perdebatannya mengenai anggapan sakral yang terjadi di tengah santri, yaitu anggapan Kiai mempunyai kasyaf yang dapat mengetahui apa saja yang dilakukan para santri di manapun dan kapanpun.
Anggapan itu bahkan digambarkan seperti ikan dalam akuarium. Seseorang akan dengan sangat mudah mengetahui gerak-gerik ikan dari luar kaca, ikan berenang ke mana, warna dan jenis apa saja akan sangat mudah dikenali. Sebab itu setiap kali santri ingin melakukan pelanggaran di pesantren pasti ragu karena menganggap Kiai melihatnya.
Bagiku itu cukup aneh. Bayangkan ada segelintir orang secara langsung mengamati segala aktivitas kita, baik yang biasa dilihat atau tidak sepatutnya dilihat. Semua orang kehilangan privasinya, bahkan tak ada ruang untuk menyembunyikan kebohongan yang sebenarnya tidak berdampak apapun pada orang lain. Tepatnya sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan.
Itulah yang diperdebatkan oleh Ahmad dan Kang Didin. Kang Didin setiap harinya membersihkan halaman pesantren secara sukarela, karena Kang Didin sendiri bukan bagian pengurus pesantren, melainkan tetangga Kiai yang rumahnya tidak jauh dari pesantren. Bisa dikatakan Kang Didin merupakan santri generasi awal. Aku sendiri menghormatinya, dia juga dengan sukarela membersihkan pesantren. Tapi aku tidak tahu kenapa Ahmad sampai meninggikan suaranya pada Kang Didin.
“Saya yang sendiri yang mengalami itu, Kang!”
“Kapan?”
“Kemarin saya dipanggil Kiai dan kata beliau, ‘dahulukan kewajibanmu dulu untuk menjaga perpustakaan, biar santri tidak sembarangan bawa buku’, padahal beliau tidak pernah ke perpustakaan. Tahu dari mana bahwa selama ini saya sering lambat menjaga perpustakaan?”
“Itu pasti ada penjelasannya, Kiai Badrun punya cara sendiri memastikan semua program di pesantren berjalan baik.” Jawab Kang Didin.
“Ini berbeda, Kang, Ustaz Sanjab bahkan selalu menyampaikan kalau kiai tahu apa yang dilakukan semua santrinya!” Ahmad sudah dua kali mengulang kalimat itu.
“Iya tahu, kalau Ustaz Sanjab yang mengatakan itu benar, tapi kalau kamu yang mengatakan itu jadi salah.” Kang Didin masih dengan suara dikontrol.
“Maksudnya?”
“Dengan keilmuan yang dimiliki Ustaz Sanjab, beliau benar mengucapkan itu.”
“Artinya saya keilmuannya kurang?”
“Bukan, yang disampaikan Ustaz Sanjab belum lengkap”
“Terus yang lengkap yang disampaikan Kang Didin?”
“Bukan begitu, sini Akang jelaskan..”
“Udahlah, Kang, lebih baik saya menghabiskan waktu di masjid saja!”
Dari jendela terlihat Ahmad meninggalkan Kang Didin begitu saja. Aku perhatikan Ahmad selalu bersikap begitu setiap kali disinggung soal pemahamannya, atau soal keyakinannya. Kenapa tidak berbincang saja dan berdiskusi dengan Kang Didin, bukannya itu lebih baik dari pada mau benar sendiri.
Sebab itu ketika Ahmad meninggalkan Kang Didin, aku langsung keluar kamar untuk mengajak Kang Didin ngobrol.
“Eh, Kang!” Sapaku, Kang Didin bersikap biasa saja, bahkan tersenyum padaku. Keseringannya Kang Didin menemani Kiai membuat Kang Didin mudah bergaul dengan para santri. “Tadi sepertinya asyik banget diskusinya.”
“Hahaha.. cuma menemani Ahmad ngobrol tentang pemahaman dia selama ini.”
“Ooh.. tentang kasyaf itu. Tadi sepertinya Ahmad cerita kalau dia dipanggil Kiai dan apa yang didauhkan Kiai memang benar-benar berhubungan dengan yang dilakukan Ahmad selama ini.”
“Iya itu, padahal Kiai sudah tentu punya cara sendiri untuk menjaga berjalannya program di pesantren. Meskipun tidak sepenuhnya ikut serta tapi beliau punya cara sendiri untuk memastikan program pesantren berjalan.”
“Itu Kang yang ingin saya sampaikan,” aku teringat kejadian beberapa hari lalu, “Kemarin saat saya ke perpustakaan ada santri minta tolong dicarikan buku karena disuruh oleh Kiai. Saat itu Ahmad tidak menjaga perpustakaan, mungkin karena kelamaan ngaji di masjid. Karena Kiai yang meminta maka aku suruh bawa saja.”
Mendengar ceritaku Kang Didin langsung tersenyum,
“Nah itu, itu yang sebenarnya terjadi. Sejak awal Kiai mungkin ingin memastikan apakah perpustakaan beroperasi atau tidak. Pasti Kiai banyak bertanya pada santri yang disuruh mengambil buku itu.”
“Iya juga ya, Kang. Pasti santri itu tidak mungkin bohong kan kalau ditanya Kiai. Kiai bertanya tentang penjaganya, banyaknya santri yang membaca dan berapa koleksi yang tersedia. Tapi dari mana Kiai tahu kalau Ahmad penjaga perpustakaan?”
“Tentu Kiai punya banyak cara, Pram. Mungkin dari cara Kiai itulah orang melihat itu kasyaf.”
“Jadi Kang Didin tidak percaya kasyaf?”
“Kang Didin percaya, tapi pada siapa keutamaan itu diberikan Kang Didin tidak tahu. Yang Kang Didin inginkan santri mengerjakan ibadah apapun di pondok karena Allah, bukan karena beranggapan Kiai mengetahuinya.”
Aku tersenyum sembari mengangguk mendengar jawaban Kang Didin, aku mulai punya pandangan sendiri tentang kasyaf yang mungkin digambarkan berlebihan oleh santri.
Keesokan harinya aku langsung menemui santri yang disuruh oleh Kiai untuk meminjam buku di perpustakaan. Aku ingin memastikan apakah Kiai bertanya tentang perpustakaan atau tidak. Dan ternyata sedikit banyak anggapanku benar, bahwa Kiai bertanya banyak hal kepada santri itu. Dan itulah yang membuat aku senang, ketika mengetahui kebenaran sesuatu dengan cara mencari tahu kebenaran aslinya.
Dan seperti biasa hari ini aku ingin menyempatkan lagi untuk berkunjung ke perpustakaan, membaca anekdot lucu untuk sekedar mengganggu pengunjung lainnya. Di tengah perjalanan Kiai lewat di jalan yang berseberangan dengan perpustakaan. Semua santri memberikan hormat dengan cara menelangkupkan kedua tangannya di depan sambil menunduk. Aku juga melakukan hal yang sama.
Kiai terlihat berbincang dengan salah satu asatid membuat santri menunggu cukup lama untuk melanjutkan aktivitasnya. Saat itulah Kiai memanggilku dengan isyarat tangan. Awalnya aku tidak yakin apakah beliau memanggilku, tapi karena sepertinya tidak ada yang lain dan semua santri menolehku, aku menghampiri beliau.
“Ka’dintoh?” Kataku pelan sambil menunduk.
“Kamu sering ke perpustakaan?” tanya beliau dengan suara jelas.
“Engki..”
“Kalau ke perpustakaan jangan hanya baca buku yang lucu-lucu, masih banyak bulu lainnya yang lebih berguna.”
Mendengar ucapan itu hatiku langsung terketuk, ingin terkejut tapi beliau seorang Kiai. Entah cara apa lagi yang digunakan Kiai, apakah Kiai mengawasi semua perilaku santrinya sampai dengan buku yang sering dibacanya? Apakah ini benar-benar kasyaf?